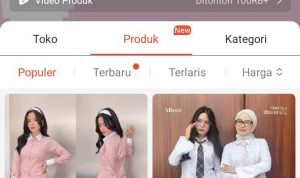Makroen Sanjaya Praktisi Media,
Mahasiswa Doktoral Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, Jakarta
NYARIS tanpa pertanda, karyawan dipangkas, pun sejumlah program pamit dari NET TV. Publik ternganga heran. NET dengan kredo “Televisi Masa Kini”, dikenal sebagai televisi dengan program berkualitas. Di kalangan milenial, NET menjadi idola. Tapi idealisme NET di tangan sang nakhoda Wishnutama takluk oleh realisme pasar. Hukum besi bisnis televisi yang sejak lama digenggam oleh sistem kapitalisme global, akhirnya memberi bukti sekali lagi; sebagus apa pun program televisi, jika berjarak dengan selera pasar, jangan harap bisa eksis. Kelindan sistem kapitalistik, dan fenomena ledakan internet serta gelembung media sosial, bisa jadi dituding sebagai kambing hitam.
Kasus NET, mungkin hanya sebuah replika dari situasi umum, yang mengendap di depan mata. Ada dua pertanyaan penting, untuk melihat masa depan bisnis media penyiaran swasta. Pertama, apakah faktor rating, share, audience reach terus menjadi variabel tunggal bagi kelangsungan hidup televisi di masa depan? Kedua, bagaimana penetrasi media dalam jaringan (daring), khususnya media sosial dalam menggoyang hegemonistik televisi yang sudah berlangsung hampir tiga dekade ini?
Kualitas versus Ekonomi Media
Sejak lama, bisnis media nasibnya ada di tangan rezim tunggal Nielsen Media Research, yang produknya berupa data kepermisaan dari 11 kota besar di Indonesia. Menurut Ade Armando, pilihan sampel di 11 kota oleh Nielsen itu tidak mewakili secara memadai populasi di Indonesia. Nielsen, kata Ade, memang tidak sedang berusaha menangkap perilaku masyarakat Indonesia, melainkan perilaku masyarakat di daerah-daerah yang paling potensial menjadi pasar bagi produsen barang (2016:76). Data kepemirsaan ini menjadi “malaikat pengadil” bahkan “malaikat pencabut nyawa” bagi suatu program televisi.
Dalam iklim kapitalistik, pebisnis tv dipaksa harus adaptif dengan konsep komunikasi internasional kontemporer, yang menurut Artz & Kamalipoui (2003:3-15) mensyaratkan adanya jalinan trilogi entitas, yaitu globalisasi, hegemoni media, dan kelas sosial, yang mengirim pesan bahwa industri tv mutlak melakukan efisiensi biaya produksi konten. Sejak berubah dari Spacetoon menjadi NET pada 2013, tv itu selalu menghuni papan tengah bawah atau tier 2 dari 14 atau 15 tv berjaringan nasional.
Pemeringkatan ini seharusnya memaksa awak tv piawai mengendalikan biaya produksi (cost production). Ketika berahi memproduksi program berkualitas menggebu, seketika jor-joran dalam biaya, di saat yang sama akan terbentur pada situasi yang tidak dikehendaki oleh globalisasi, yaitu efisiensi. Pelaku industri tv mutlak memahami hukum ekonomi media, yang menurut Philip M.Napoli (2009) membantu untuk mengerti faktor pembentuk evolusi, perilaku, keluaran konten, dan paling pokok dampak dari industrialisasi media. Sebanyak apa pun anggapan bahwa media adalah entitas politik dan budaya, tetapi yang paling perlu dicamkan adalah media merupakan entitas ekonomi.
Pebisnis tv agaknya belum menganggap serius ancaman media baru (new media), yang oleh Holmes (2015:21) diistilahkan sebagai era media kedua (second media age) yang bersifat interaktif, meninggalkan era media pertama (first media age) yang bersifat broadcast (penyiaran). Terdapat enam perbedaan historis antara media lama versus media baru. Pertama, terletak pada sentralisasi versus ketersebaran. Kedua, komunikasi satu arah versus dua arah. Ketiga, cenderung dikontrol negara versus menghindari kontrol negara. Keempat, media lama menciptakan stratifikasi dan ketidaksetaraan versus media baru yang menciptakan demokratisasi. Kelima, media lama terfragmentasi dan dipandang sebagai massa versus media baru yang bersifat individualitas. Keenam, media lama memengaruhi kesadaran versus media baru memengaruhi pengalaman individu tentang ruang dan waktu.
Disrupsi, Mediamorfosis , atau Konvergensi?
Disrupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hal yang tercerabut dari akarnya. Istilah disrupsi, atau diumpamakan sebagai “mengganggu” atau “merusak” tatanan, kali pertama diperkenalkan Joseph L. Bower dan Clayton M. Christensen pada artikel berjudul “Disruptive Technologies: Catching the Wave” 1995 (Semantic Scholar: 1995). Disrupsi inovasi menjelaskan, bagaimana kerja teknologi yang mengganggu dan dampaknya terhadap para pemimpin industri. Tapi terma disrupsi inovasi ini belum terlalu dikenal oleh pelaku media. Pebisnis media, baru secara samar mendengar istilah mediamorfosis, atau sesekali membicarakan konvergensi media. Sedangkan mediamorfosis, yang diperkenalkan Roger Fidler melalui bukunya “Mediamorfosis: Understanding New Media” (1997), diartikan sebagai transformasi media komunikasi, yang biasanya ditimbulkan hubungan timbal balik yang rumit antara berbagi kebutuhan yang dirasakan, tekanan persaingan dan politik, dan berbagai inovasi sosial serta teknologi.
Televisi swasta di Indonesia belum ada yang berani melakukan mediamorfosis dalam konteks menajamkan genre program. Umumnya positioning tv swasta, berkecamuk di genre general entertainment, yang diibaratkan pasar serbaada (super market). Genre news and information, yang menyediakan niche-audience, sekarang diperebutkan Metrotv, tvOne, Kompastv, dan iNews , dengan ceruk audiens yang relatif statis.
Konvergensi media, berarti konsumen mendapatkan beberapa layanan melalui satu platform atau perangkat atau mendapatkan layanan tertentu pada beberapa platform atau perangkat. Tim Dwyer (2010,4) menjelaskan, dalam konteks di mana “konvergensi ada di sekitar kita—ponsel dengan video, radio dan internet, radio melalui platform tv dan internet dan tv melalui platform mobile termasuk radio digital, dan internet–semua difasilitasi oleh teknologi digital yang bergerak”. Alih-alih melakukan metamorfosis, semua tv swasta di Indonesia yang melakukan konvergensi media, hanya sekedar latah, mengikuti tren atau bahkan disalahgunakan oleh kekuatan politik.
Pelaku bisnis tv swasta bukan tidak adaptif maupun antisipatif. Semua entitas tv, memiliki “saudara kembar” berupa situs web atau akun media sosial, dan sebagian lagi membangun bisnis konvergensi media. Tetapi platform situs web, dan juga kanal di YouTube belum dapat dikapitalisasi secara ekonomis. Sebagian lainnya justru bersifat parasitasi. Rezim tunggal pemeringkatan tv masih bersifat hegemonistik, dan tak memungkinkan platform lain eksis, apalagi bertumbuh.
CEO Google Eric Schmidt dan Direktur Google Ideas Jared Cohen, lima tahun silam melontarkan prediksinya bahwa “tak lama lagi, semua orang di bumi akan terhubung. Dengan lima miliar orang lagi yang siap merambah dunia maya, ledakan konektivitas digital akan menghasilkan peningkatan dalam produktivitas, kesehatan, pendidikan, kualitas hidup, dan berjuta kesempatan lain di dunia nyata” (2014:1). Betul saja, manifesto internet berupa media daring; yang di dalam lambungnya terdapat media sosial, telah merangsek jauh ke semua lapisan, melintasi batas geografis dan demografis.
Data Hootsuit: We Are Social 2019 cukup mencengangkan tapi banyak orang abai, bahwa penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 56% atas populasi, ekuivalen 150 juta pengguna. Pengguna media sosial aktif juga di kisaran 150 juta. Konsumsi media sosial per hari 3 jam 26 menit (katadata :2019). Adapun tingkat kepercayaan media sosial sebagai penyedia berita, secara global mencapai 35%, dibanding penggunaan media arus utama berkisar 50-55 persen (Digital 2019:Australia).
Media digital dengan media konvensional saling melengkapi (https://www.Nielsen.com, 14 Februari 2018). Konsumen media arus utama juga mengonsumsi media digital. Tapi yang mencemaskan, 42% pemirsa tv juga mengakses internet. Durasi konsumsi media digital pun meningkat dalam tiga tahun terakhir, dari 1 jam 52 menit (2014) menjadi 3 jam 8 menit (2017).
Pada 2019 durasi itu naik lagi menjadi 3 jam 26 menit (Hotsuite: We Are Social 2019), ditambah dengan tingkat kepercayaan terhadap media sosial sebagai sumber pencarian berita secara global sudah mencapai 35%. Pelan tapi pasti YouTube mengambil alih hegemoni tv. Jangan-jangan senja kala tv swasta, tak lama lagi berkelebat, seperti yang terjadi pada media massa cetak sejak sepuluh tahun terakhir.
Artikel ini telah tayang di nasional.sindonews.com