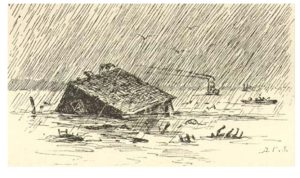Oleh : Jhony Howord, Wahana Generasi Aceh
Lembaga Wali Nanggroe dibentuk sebagai implementasi salah satu butir MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM di Helsinki (15 Agustus 2005). Lembaga tersebut menjadi ikon yang begitu istimewa disaat membahas ke-Acehan. Muncul pertanyaan besar yang tidak kunjung hilang yaitu, apakah Aceh butuh Wali Nanggroe?
Lembaga kekhususan Aceh yang di pimpin oleh paduka yang mulia Malik Mahmud Al Haythar itu tidak lepas dari pro dan kontra hingga saat ini karena dinilai tidak demokratis dan dikuasai oleh sekelompok elit Aceh. Walaupun pada dasarnya lembaga itu diharapkan bisa diterima oleh segenap lapisan masyarakat Aceh.
Lembaga yang disebut dalam Undang-Udang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai lembaga yang mengatur kepemimpinan adat dan bertindak sebagai pemersatu rakyat Aceh masih belum mampu berjalan dengan baik.
Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Disebutkan Wali Nanggroe memegang jabatan selama 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Namun, pasal itu akan direvisi dengan menghapus batasan masa jabatan sehingga Wali Nanggroe bisa seumur hidup. Walaupun belum disahkan tetapi hal serupa sudah disampaikan lansung oleh Malik Mahmud dalam unggahan Video YouTube dari akun Refly Harun dengan judul XKLUSIF! WALI NANGGROE ACEH KELUARIN SEMUA UNEG-UNEGNYA pada menit 08:50, seolah-olah revisi itu sudah sah dan diterima oleh masyarakat Aceh.
Pada akhir masa jabatan sebelum nya juga muncul polemik dan sorotan terhadap APBA Tahun 2018 yang dialokasikan anggaran melalui Keurokon Katibul Wali (Sekretatiat Lembaga Wali Nanggroe Aceh) sebesar Rp 32,6 miliar yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 4,7 miliar dan belanja langsung sebesar Rp 27,8 miliar. Dengan penggunaan APBA sebesar itu muncul pertanyaan, apa yang sudah diberikan untuk Aceh oleh Lembaga Wali Nanggroe?
Secara Legitimasi Lembaga Wali Nanggroe sudah banyak menerima penolakan, dan secara otoritas juga menuai banyak polemik di masyarakat Aceh. Sehingga lembaga yang seharusnya mengakomodir seluruh kepentingan rakyat Aceh seolah pincang.
Wacana Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) walaupun dengan dalih pembenaran apapun tetap sebagai bentuk sebuah perpecahan dan gagalnya Wali Nanggroe dalam menyatukan rakyat Aceh. Masih ada Aceh yang merasa diasingkan oleh Aceh, masih ada Aceh yang merasa tidak dipedulikan oleh Aceh, masih ada Aceh yang merasa dibodohi oleh elit politik nya Aceh.
Jika masyarakat disuruh memilih uang 300 ribu atau angkat tangan dalam mendukung Wali Nanggroe akan banyak yang memilih uang, karena paradigma yang sudah terbentuk pada sebagian masyarakat bahwa lembaga itu milik sekelompok elit Aceh bukan milik masyarakat Aceh. Hari ini yang masih melihat keistimewaan dan kekhususan lembaga itu cuma sebagian dari rakyat Aceh, bukan karena krisis identitas dan pemahaman sejarah tetapi karena eksistensi lembaga itu gagal dihati masyarakat Aceh.
Aceh sudah merajuk banyak peristiwa untuk sampai pada detik ini, pertumpahan darah dan nyawa menjadi saksi bagi Aceh. Sebuah opini yang dipublikasi oleh Acehreal_ pada media sosial nya juga memberikan kesan bahwa Aceh sedang tidak baik-baik saja. Sultan Daud, T. Panglima Nyak Makam, Teungku Chik di Tiro, Daud Beureu’eh, Cut Nyak Dhien, Teuku Umar, Cut Nyak Meutia, Teungku Fakinah, Teungku Chik Kuta Karang dan ratusan ribu pejuang Aceh lain nya mengorbankan nyawa untuk mempertahankan kedaulatan aceh.
Semangat yang sama pada Teungku Hasan di Tiro bersama sebagian pejuang GAM, seharusnya Aceh sudah di posisi Self Government bukan cuma sebatas daerah otonomi yang bisa dicabut kapan saja oleh pemerintah pusat. Hal ini juga pernah dibahas sebelum nya oleh Sufriadi dalam Tesis nya berjudul Wali Nanggroe dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan akan terus berlanjut oleh generasi berikutnya hingga evaluasi atau bubarnya lembaga itu.
Masyarakat Aceh menunggu posisi Self Government Aceh seperti opini Martti Oiva Kalevi Ahtisaari. Dalam opininya, Self-Government disebut sebagai kewenangan yang berada satu tingkat di atas otonomi khusus. Dicontohkannya seperti Pulau Aland di Finlandia, dimana bahasa resmi daerah itu adalah bahasa Swedia, berbendera sendiri, bahkan disebut semua kapal angkatan laut dan pesawat udara Finlandia harus meminta izin pemerintah Aland terlebih dahulu sebelum masuk atau melintasi Aland.
Tapi Aceh jauh dari kata itu, Aceh sekarang bukan lagi wilayah berdaulat melainkan sebuah Provinsi di ujung Utara Sumatra.
Secara kolektif seharusnya kita mampu memperjuangkn kedaulatan rakyat melalui wadah Lembaga Wali Nanggroe dan seharusnya mampu mengejar ketertinggalan dan melampaui wilayah-wilayah maju di indonesia. Namun, kelompok elit Aceh seolah terbuai dengan rasa kenyamanan yang dibungkus rapi oleh kata Daerah Istimewa sehingga tidak melihat lagi apa yang dibutuhkan oleh rakyat Aceh.
Kelembagaan Wali Nanggroe harus dipertahankan karena merupakan salah satu kekhususan bagi Aceh, namun secara mayoritas masyarakat di Aceh tidak memerlukan Wali Nanggroe. Masyarakat lebih membutuhkan pembangunan ekonomi secara merata dan terjaga perdamaian Aceh.
Tidak bisa dipungkiri, jika kondisi Wali Nanggroe yang apatis terhadap subtansi kemaslahatan dan kesejahteraan semua etnik Aceh masih terus berlanjut maka akan ada gejolak pembentukan Wali Nanggroe tandingan.
Dibutuhkan atau tidak lembaga itu di Aceh bukan berarti anti perdamaian di Aceh. tetapi jika lembaga itu tidak kunjung di evaluasi maka itu faktor yang seharusnya menjadi anti perdamaian dan pemersatu masyarakat Aceh.
Saat ini Aceh butuh upaya masyarakat untuk mengevaluasi lembaga yang disebut sebagai pemersatu rakyat Aceh itu, bukan pembunuhan karakter sang Wali Nanggroe di hati dan batin rakyat, melainkan bagaimana pola kerja Wali Nanggroe yang harus didiskusikan sesuai subtansinya agar legitimasi dan otoritasnya berjalan dengan baik. Seorang yang dituakan tetapi tidak didengarkan secara mayoritas maka itu disebut kemunafikan.