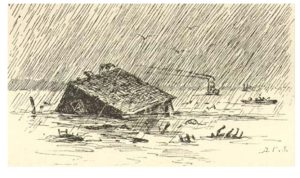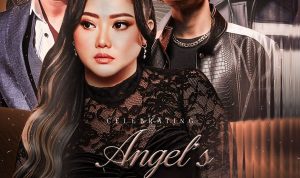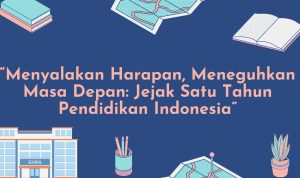Beberapa waktu lalu ada perbedatan sengit yang menggoncangkan KluBuku jagad #Asgard. Para Asgardian (demikian saya menyebut member-member WAG #Asgard) membahas polemik mana yang lebih penting antara konten (isi) dengan narasi sebuah tulisan? Sebagian Asgardian yang mementingkan isi masuk kubu isi, sebagiannya lagi yang mementingkan narasi masuk kubu narasi.
Kubu narasi mendasari pada argumen bahwa kita sekarang hidup di era banjirnya informasi di mana konten melimpah ruah dan sangat mudah didapatkan. Dan sesuatu yang sangat mudah didapatkan cenderung mudah pula diabaikan dan dilupakan. Agar tidak mudah diabaikan dan dilupakan maka pengemasan narasi yang unik diperlukan.
Sebagai contoh, jika Anda membuat tulisan yang berisi kewajiban khilafah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadits, itu konten, itu isi. Tapi narasinya apa? Kisah apa yang Anda ceritakan untuk men-deliver konten tadi? Back stories-nya relevan tidak? Cara bertutur Anda otentik tidak? Semua narasi tadi yang akan menentukan apakah tulisan Anda menginspirasi atau tidak.
Lalu kubu isi menyanggah; apa gunanya narasi jika tanpa fondasi serta dasar pemikiran yang kuat? Tulisan yang terlalu mengedepankan narasi tanpa pondasi yang kokoh hanya akan membuat pembacanya melayang-layang gak jelas. Lalu dijawab lagi oleh kubu narasi; kami tidak bilang konten atau isi tidak penting. Asumsinya tulisan tersebut sudah selesai dengan urusan konten yang standard dan syar’iy.
Lalu argumen kubu narasi tadi disanggah lagi; kalau begitu statement narasi lebih penting dari isi hanyalah ungkapan hiperbolik. Kubu narasi nampaknya tidak terima dibilang hiperbola. Tapi mereka kelihatan enggan memperpanjang debat dan hanya bilang; if you say so. Kurang lebih dalam bahasa jawa maksudnya adalah; sak karepmu lah.
Salah seorang punggawa Asgardian jebolan pesantren (dan sekarang jadi pemimpin pesantren ternama di Jogja), nampaknya masih belum puas dengan semua argumen kubu narasi. Dia mengeluarkan amunisi kutipan dari kitab-kitab klasik pesantren: الأصل في الكلام هو الحقيقة “Hukum asal pemaknaan sebuah kalimat adalah makna hakikinya (isinya), bukan makna majazinya (narasinya).”
Salah seorang punggawa Asgardian lain, yang sekaligus seorang arsitek (dari profesinya kita tentu tahu mereka mengedepankan desain dan estetika), mencoba menengahi dengan meminjam argumen buku Homo Deus karangan Yuval Noah Hariri. Bahwa ada dua tipe manusia; manusia yang mengalami dan manusia yang bercerita. Terkadang diri yang mengalami itu berbeda dengan diri yang bercerita. Intinya sang arsitek menekankan pentingnya narasi dan isi yang kuat dan otentik.
Nampaknya Asgardian jebolan pesantren tadi masih belum puas. Kalau barusan kubu narasi mengutip argumen sejarawan Yuval Noah Hariri, tak mau kalah dia mengutip argumen sastrawan Cak Nun alias Emha Ainun Najib, lewat tulisannya yang sempat viral: “Pilih Kutang 36B Atau Isinya 36B?”. Saya bisa merasakan sebagian besar member KluBuku Asgardian, termasuk saya, memijat-mijat kening mereka setelah membaca judul tulisan Cak Nun tadi.
Nampaknya tulisan Cak Nun tadi berhasil membuat situasi diskusi menjadi sunyi. Saya tidak tahu apakah kesunyian tadi mengarah kepada titik temu, atau mengarah kepada hal lainnya. Namun yang pasti statement Cak Nun “pilih kutang atau isinya” menjadi semacam common ground atau pijakan bersama dalam babak diskusi selanjutnya.
Sahabat saya yang pimpinan pondok pesantren tadi mencoba mengkerucutkan diskusi dengan mengutip closing statement Cak Nun: “Utamakanlah isinya, serta tetaplah merawat kemasannya dengan baik.” Salah seorang Asgardian lain menambahkan, “Sekalipun demikian, biasanya sebelum kita menyantap isinya, kemasan memainkan peranan yang sangat penting. Istilahnya, buka sitik joss!” Saya menambahkan, inilah mengapa produk lingerine jadi laris manis, serta perusahaan underwear Victoria’s Secret menjadi perusahaan multi million dollar.
Lalu Asgardian lain menyahut, “Tapi bukankah isinya itu qadha atau takdir yang harus diterima dengan penuh kerelaan dan tidak bisa diotak-atik lagi? Sehingga wilayah ikhtiyar kita adalah bagaimana mengemas dan menghiasnya sebaik mungkin?” Saya buru-buru menjelaskan maksud statement tersebut: “Kembali kepada contoh penegakan khilafah sebelumnya adalah wajib, ini sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Tapi bagaimana men-deliver kewajiban tadi agar orang-orang merasa terinspirasi, bergegas dan bergairah dalam memperjuangkannya, di sinilah pentingnya sebuah narasi.” Saya bisa merasakan sebagian besar yang menyimak mangut-mangut paham.
Nampaknya titik temu dan sinergi antara isi dan narasi sudah benar-benar mengkerucut. Isi adalah fondasi dan dasar pemikiran yang sudah baku. Sedangkan narasi adalah kombinasi antara alur, cerita latar, diksi yang berbaur dinamis dengan sentuhan pribadi dan cara khas penulis membawakan tulisannya. Narasi itu unik. Narasi itu story telling. Sinergi antara isi dan narasi yang kuat adalah ruh dari tulisan yang menginspirasi, menggugah dan menggerakkan.
Pembaca tulisan kita tidak bodoh. Ekspektasi mereka tinggi. Waktu mereka berharga. Mereka tidak suka membuang-buang waktu membaca tulisan yang isinya sudah mereka ketahui, bahkan sebelum mereka selesai membaca. Dan ketika mereka tidak suka, mereka tidak akan pernah kembali membaca tulisan Anda. Apa yang lebih menyedihkan dari terputusnya amal jariyah atas orang-orang yang membaca tulisan kita?
Ketika mereka mau membaca. Dalam hati mereka berkata: Kejutkan saya, buat saya penasaran, beritahu saya hal baru, puaskan logika saya, buat saya terharu, pantik semangat saya, dan buat saya tersenyum, dari hati. Jika semua ekspektasi mereka terpenuhi, mereka akan mulai memperhatikan tulisan Anda. Dan jika Anda cukup konsisten mengulangi pola di atas, tidak menutup kemungkinan mereka akan jadi pembaca setia Anda. Dan ini adalah ladang amal jariyah yang diimpi-impikan para pencari surga.
Selamat berkarya meramu isi dan narasi! Oleh: Yuda Pedyanto