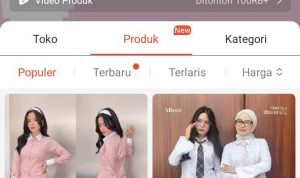Oleh: Luthfi Assyaukanie (Lecturer)
Setelah berpikir panjang dan diselimuti keraguan, akhirnya saya memutuskan kembali ke tanah air. Rencananya, program fellowship saya baru akan berakhir pada Juli 2020. Tapi, melihat situasi pandemi yang semakin buruk, saya memilih balik ke Indonesia dan melanjutkan pekerjaan dari Jakarta. Toh, di Washington DC, saya tidak bisa ke mana-mana, bekerja dari rumah, menghadiri rapat-rapat lewat Zoom dan berkordinasi lewat email, sesuatu yang semuanya bisa saya lakukan dari Indonesia.
Masalahnya, sejak tanggal 24 April, pemerintah Indonesia memberlakukan pelarangan mudik, yang berarti juga menghentikan jalur penerbangan. Tidak ada pesawat ke Indonesia. Itu yang pertama saya dengar. Tapi, saya tidak putus asa. Saya menghubungi Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di DC, yang seluruh stafnya bekerja dari rumah. Saya diberikan nomor khusus untuk bertanya seputar urusan kepulangan bagi WNI yang berada di AS.
Setelah mendapatkan kepastian bahwa bandara Jakarta tetap buka bagi penerbangan internasional, saya mencari pesawat dan menyiapkan dokumen kepulangan. Akhirnya, saya mendapatkan penerbangan pada tanggal 30 April, dengan rute DC – San Francisco – Narita – Jakarta. Di luar dugaan, perjalanan cukup lancar meski sangat sepi. Di sepanjang koridor bandara San Francisco yang besar, saya berjalan seorang diri, menuju gerbang keberangkatan. Seluruh gerai tutup dan tak ada petugas satu pun yang tampak.
Pesawat Boeing 787 yang besar hanya berisi kurang dari 30 orang. Saya bisa tiduran di tiga kursi dengan melonjorkan kaki. Jarang-jarang naik pesawat jarak jauh dengan kabin yang lengang. Setelah menempuh perjalanan 26 jam lebih, saya tiba di bandara Soekarno-Hatta, yang juga sangat sepi. Protokol ketibaan sudah disiapkan bagi WNI yang pulang. Setelah melewati beberapa meja pengecekan kesehatan akhirnya saya bisa keluar. Tiba di rumah sekitar jam 2 pagi menjelang sahur.
Silang Pendapat. Saya tiba di AS pada akhir Februari dan sempat menikmati “situasi bebas” selama sekitar dua minggu. Pertengahan Maret, kebijakan bekerja dari rumah diberlakukan. Sebagai ibu kota negara, Washington DC memberlakukan tindakan yang ketat dalam mengantisipasi penyebaran Corona. Apalagi pada pertengahan Maret, New York dinyatakan sebagai pusat wabah. New Jersey menjadi negara bagian kedua dengan korban terbanyak. Washington DC hanya terpisah dua negara bagian dari New York, yakni Maryland dan Pennsylvania. Saya sendiri tinggal di perbatasan antara DC dan Maryland.
Ketika wabah melanda New Jersey, penduduk Maryland panik. Begitu juga DC. Mereka khawatir, wabah akan segera menghampiri mereka. Berbagai kebijakan baru dikeluarkan, seperti pewajiban pemakaian masker di luar rumah, khususnya di super-market. Toko-toko tutup, kecuali yang terkait dengan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Semakin hari susasana semakin mencekam.
Hampir 24 jam, isi berita di stasiun-stasiun televisi tentang Corona. Dan hampir setiap hari Gedung Putih menggelar konferensi pers untuk memberikan update tentang pandemi ini. Saya mengikuti perkembangan krisis di Amerika lewat stasiun televisi itu, selain dari berbagai sumber, termasuk diskusi-diskusi online dengan sejumlah orang. Dari semua negara bagian di Amerika Serikat, yang paling sering muncul dalam liputan media adalah New York. Selain menjadi pusat pandemi, New York memiliki gubernur yang sangat komunikatif dan pendekatannya terhadap krisis sangat empatik, yang menarik perhatian banyak orang.
Di DC dan Maryland, saya tidak merasakan kecemasan dan kepanikan seperti yang tampak di New York. Pada minggu-minggu pertama hingga pertengahan April, DC dan Maryland relatif longgar. Meski sebagian besar toko tutup, transportasi publik tetap jalan. Saya masih bisa menggunakan Metro (kereta bawah tanah) dan bus dalam kota. Situasi mulai sepi dan sedikit mencekam baru terjadi menjelang minggu keempat April. Saat itu, walikota DC mulai memberlakukan kebijakan wajib mengenakan masker.
Presiden Trump hampir setiap hari muncul di televisi, mengeluarkan pernyataan dan memberikan arahan-arahan terkait penanganan pandemi. Para pembantu utamanya, khususnya yang terkait dengan gugus tugas penanggulangan wabah Corona, selalu mendampinginya. Dua ahli hadir bersamanya, hampir tak pernah absen, memberikan update seputar wabah, yakni: Dr Anthony S. Fauci, Direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases, dan Dr. Deborah Leah Birx, Kordinator Respon untuk urusan Corona. Gugus tugas penanganan terhadap wabah Corona sendiri dipimpin oleh Wakil Presiden, Mike Pence.

Dalam konferensi pers, beberapa kali terjadi ketidaksinkronan informasi atau pernyataan yang saling bertentangan antara Presiden Trump dan para pembantu medisnya. Sejak awal, pemerintah Amerika Serikat memang seperti ragu-ragu dalam menyikapi wabah ini. Ketika dokter Fauci menjelaskan bahwa jumlah korban yang sangat banyak semestinya bisa diatasi jika pemerintah mengambil keputusan lebih dini, presiden Trump menyanggahnya dan para pendukung fanatik Trump meresponnya dengan keras. Di media sosial beredar hashtag PecatFauci (#FireFauci) karena pernyataannya dianggap menyudutkan Trump. Isu ancaman pembunuhan terhadap dokter Fauci sempat beredar luas.
Trump juga beberapa kali membuat blunder dalam konferensi persnya. Selain selalu mengklaim bahwa Amerika merupakan negara terbaik dalam menangani Corona –yang tentu saja tidak benar– Trump menganjurkan cara agar tim kesehatan mencoba menanggulangi virus dengan cara menginjeksi disinfektan (cairan pembersih lantai atau pencuci piring) ke tubuh manusia. Pernyataan gegabah ini diulas di CNN berhari-hari dan menjadi bahan tertawaan banyak orang. Meski kemudian Trump meralat pernyataan itu dengan mengatakannya sebagai sarkasme, tak ada orang yang mempercayainya.
Ketika jumlah kematian terus meningkat dan angka korban positif mendekati 1 juta, Trump berdalih bahwa itu karena Amerika melakukan tes sangat besar, terbanyak dibanding negara-negara lain. Pernyataan ini pun langsung disanggah banyak orang dan menjadi bahan bully-an di televisi dan media sosial. Tentu saja, pernyataan Trump tak berdasar, karena secara perkapita, jumlah tes yang dilakukan di Amerika jauh lebih rendah ketimbang negara-negara lain. Hingga awal Mei, Amerika berada di urutan ke-40 negara yang paling banyak melakukan tes per 1 juta penduduk. Israel, Jerman, Denmark, dan beberapa negara Eropa lainnya berada di atas Amerika dalam hal jumlah tes perkapita.
Menyaksikan bagaimana pemerintah federal Amerika Serikat menangani Corona seperti menyaksikan sirkus yang tengah beratraksi dengan momen-momen penuh suspensi. Presiden Trump kerap mengeluarkan pernyataan yang lebih banyak menuai kontroversi ketimbang menenangkan. Ketika penasihat medisnya mendesak agar kebijakan pemakaian masker segera diumumkan, Trump melakukannya sambil berkomentar “I don’t think I’ll do it” (saya kira saya tak akan mengenakannya). Trump memang kemudian tak pernah terlihat memakai masker. Wakil Presiden Pence juga tak mengenakan masker ketika mengunjungi sebuah klinik kesehatan di Minnesota, seolah-olah ingin mengikuti jejak Trump melawan kebijakannya sendiri tentang pemakaian masker.

saat berkunjung ke sebuah klinik kesehatan. Foto: Reuters.
Sejak awal, pemerintahan Trump memang kurang bersemangat dengan tindakan penguncian (lockdown) atau kebijakan apapun yang mengurangi pergerakan manusia. Dia tampak sangat khawatir kalau pembatasan sosial bisa berakibat buruk bagi ekonomi Amerika. Karena itulah, ketika dampak ekonomi mulai terasa, dengan semakin besarnya jumlah pengangguran baru (dalam dua minggu pertama angka pengangguran bertambah 14 juta. Kini jumlahnya mencapai 27 juta orang), Trump tak ragu-ragu untuk melancarkan paket stimulus ekonomi. Biasanya Republik adalah partai yang anti-subsidi, tapi karena ini menyangkut nasib ekonomi negara, Trump dan partainya sepakat menggelontorkan subsidi sebesar 3 triliun USD (45 ribu triliun rupiah).
Sebagaimana di negara-negara lain, persebaran wabah Corona di Amerika tidak merata. Episentrum wabah terjadi di New York dengan korban meninggal lebih dari 26 ribu orang. Negara bagian kedua dengan jumlah kematian terbanyak adalah New Jersey, tetangga New York, dengan 8000 lebih kasus. Negara-negara bagian lainnya, relatif kecil. Perbedaan data korban ini yang memunculkan perselisihan dalam menyikapi wabah. Ada beberapa negara bagian yang tidak terlalu keras dalam mengambil tindakan. Ada yang sangat berhati-hati. Georgia adalah negara bagian yang paling rileks dalam menghadapi wabah. Sejak 21 April, gubernur negara bagian ini sudah mengumumkan akan segera membuka perkantoran dan bisnis.
Keputusan kapan pembatasan sosial sebaiknya dihentikan menjadi perdebatan serius di Amerika. Perdebatan ini bahkan memunculkan ketegangan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Presiden Trump menegaskan kalau keputusan membuka atau menutup pembatasan adalah wewenang pemerintah pusat (federal). Tapi, Andrew Cuomo, gubernur New York, membantahnya dan menyatakan bahwa wewenang itu ada pada negara bagian, bukan pemerintah pusat. Sejumlah ahli hukum dan tata-negara turun tangan, meramaikan perdebatan seputar batas-batas wewenang konstitusional ini.
Penanganan Krisis. Perdebatan antara pengambil kebijakan, pakar, politisi, dan pengamat, seputar wabah Corona di Amerika Serikat merefleksikan penanganan negara itu terhadap pandemi ini. Keterlambatan dalam mengambil keputusan berujung pada melonjaknya angka kematian dan jumlah orang yang terjangkiti virus. Amerika adalah negara dengan jumlah kematian akibat Covid-19 terbesar di dunia. Hingga 8 Mei, berdasarakan catatan Worldometer, angkanya mencapai 76.942 jiwa. Sedangkan jumlah orang yang positif terkena virus mencapai 1.292.879 orang.
Amerika bukan satu-satunya negara yang terlambat dalam mengambil keputusan. Hampir semua negara baru menyikapi isu ini secara serius dua bulan setelah virus ini meledak di Wuhan, China. Tak ada orang yang menyangka bahwa wabah Corona akan menjalar begitu cepat dan massif di luar China. Peringatan dari para ahli medis agar berhati-hati dan waspada dimaknai sebagai pernyataan umum saja, sebagai warning biasa. Tak ada yang menyangka kalau negara-negara maju tampak begitu kewalahan, tak siap dengan serangan yang datang tiba-tiba.
Kurangnya ventilator dan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis menjadi isu utama dalam penanganan pandemi ini di Amerika Serikat. Beberapa dokter dan perawat di rumah sakit bahkan tidak menggunakan APD dan masker, karena tidak ada persediaan sama sekali. Kelangkaan APD ini sempat menuai keluhan dan membuat putus asa beberapa tenaga medis. Salah seorang dokter yang bekerja di unit darurat penanganan Corona, Lorna M. Breen, mengakhiri hidupnya, karena tak sanggup melihat jumlah korban dan kurangnya peralatan bagi tenaga medis. Kasus bunuh diri dokter di New York ini bagaikan palu yang memukul keras cara-cara penanganan Corona di AS (The New York Times, 27/04/2020).
Jangankan ventilator dan APD, hal yang paling sederhana saja, seperti masker, sangat sulit didapat. Sejak awal April saya berkeliling ke puluhan apotek dan toko di DC dan Maryland untuk mencari masker. Tak satupun memiliki persediaan. Akhirnya saya memutuskan membeli secara online, dengan harga yang cukup mahal. Tapi, sampai saya kembali ke Indonesia, pesanan online itu tak pernah sampai. Ketika menuju Bandara, supir Taxi yang membawa saya tak mengenakan masker. Dia enggan membeli masker, katanya, karena satu masker sekali pakai, harganya 14 dolar.
Jika mengingat perjuangan mencari masker di DC, saya merasa bersyukur hidup di Indonesia. Di sini, kelangkaan masker dengan cepat bisa diatasi karena masyarakat dengan segera berlomba-lomba membuatnya, dari berbagai macam bahan. Di Amerika, tidak ada inisiatif untuk itu. Hanya rumah tangga yang memiliki mesin jahit yang membuatnya untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya. Mereka yang tak punya mesin, menggunakan pengganti masker seadanya, seperti sal dan sapu tangan.
Pengalaman tinggal dua bulan di Amerika Serikat memberikan penjelasan kepada saya mengapa negeri adidaya itu memiliki begitu banyak korban dan mengapa penanganannya tampak berantakan. Diam-diam, saya bersyukur pada apa yang dilakukan pemerintah dan masyarakat kita di Indonesia, tentu dengan segala kekurangannya. Saya melihat, penanganan Corona di Indonesia lebih baik dari apa yang saya saksikan di Amerika Serikat.
Penulis adalah Peraih PhD dari Universitas Melbourne, Australia dalam bidang Sejarah Politik. Luthfi adalah pendiri dan CEO Qureta. Mengajar Hubungan Internasional di Universitas Paramadina, Jakarta.
Tulisan ini dimuat juga di Lestarimoerdijat.com