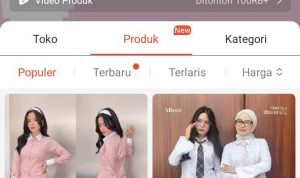Jika saya menyebut sampah, maka apa yang melintas di benak kalian? Busuk? Kotor? Sumber penyakit? Seperti itulah sampah. Tetapi, bagi secuil orang, sampah malah bisa menjadi berkah. Tumpukan sampah yang dihasilkan orang pun bisa mendatangkan rezeki tak dinyana untuk orang lain.
Orang yang membuang sampah akan menganggap sampah tak berguna lagi. Layak dibuang, ditelantarkan, dan membiarkan orang lain yang punya hasrat dan bakat menjadi pemulung dan pendaur ulang untuk memungutnya.
Makin canggihnya peradaban manusia, sampah bukan cuma yang berwujud fisik, seperti plastik yang selalu jadi musuh utama umat manusia. Melainkan komentar dan tweet juga bisa menjadi sampah.
Tiap hari setidaknya kita (eh, kita?) membuang dua jenis sampah, ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berbeda pula. Pertama, sampah fisik yang kita tak perlu bertanggung jawab membuangnya hingga ke TPA, sebab kebanyakan orang begitu. Kedua, sampah di media sosial macam komentar dan tweet yang harus dipertanggungjawabkan bila dilaporkan dengan UU ITE.
Oleh sebab terlalu eufemistis, dan mudah tersinggung, maka istilah sampah untuk komentar dan tweet diperhalus. Dibuat supaya kita nggak kelihatan sedang membuang sampah. Meski hakekatnya hal tersebut tetaplah sampah. Tapi karena terlalu santun, kita menggebu-gebu menamainya dengan sebutan “kritik”, “kebebasan berpendapat”, atau “demi bangsa dan negara”.
Begitulah aktivitas orang-orang yang bersembunyi di ketiak akun Twitter—entah alter atau bukan—yang hobinya beradu tagar. Jika Twitter bagai tempat penampungan sampahnya, sedangkan mereka yang beradu tagar supaya jadi nomor satu di trending itulah pembuang sampahnya, dan tweet-nya adalah sampah. Maka aktivitas menaikan tagar ini ya eufemisme dari aktivitas nyampah.
Kedua jenis sampah ini memang berdampak buruk, sama-sama menimbulkan pencemaran dan ketidaknyamanan. Tapi nyampah gaya baru berupa beradu tagar jarang sekali dipermasalahan atau seminimal-minimalnya diperlakukan buruk, sama seperti orang yang buang sampah sembarangan di kali, pinggir jalan, atau sepanjang jalan raya.
Nyampah lingkungan lebih sering dibenci, disumpah serapahi, sampai-sampai orangnya dilabeli tak cinta lingkungan, perusak lingkungan, ujungnya dianggap tak memikirkan anak cucu, padahal yang nyampah masih cucu-cucu. Sementara nyampah dengan adu tagar tidak, tak mungkin juga dianggap mencemari Twitter, malahan banyak yang ikut-ikutan. Jarang muncul pelabelan perusak di sana.
Ajaibnya, mereka yang kerjaannya beradu tagar di Twitter ini enggan disebut nyampah. Orang nyampah itu kan sebenarnya nggak perlu dilihat dari status sosialnya, gendernya, atau tua-mudanya. Siapa saja yang membuang sampah seenaknya, dia nyampah. Namun perang tagar ini lain. Beda urusan.
Andai dia buzzer, maka baru boleh disebut nyampah. Tetapi jika orang tersebut nggak mengaku dirinya buzzer, misal murni dari lubuk hati yang paling dalam pengin andil beradu tagar ya dilarang disebut nyampah. Kendati aktivitas keduanya sama: berusaha menaikan tagar.
Sejak corona masuk Indonesia, dan kurvanya tak kunjung melandai. Sebab, kebijakan yang mbulet bagai sinetron Indosiar, adu tagar mulai berkecamuk di jagat Twitter. Iya, adu tagar yang cuma eufemisme dari kata nyampah tadi. Mula-mula muncul #SayaPercayaJokowi, terus sebelum saya menulis ini mencuat tagar #BisaKerjaTapiBoong dan #MerakyatTapiBoong, adaptasi dari trending kasus Ferdian Paleka.
Urusan tagar-tagar itu objektif tidaknya, subjektif tidaknya, berasal dari buzzer atau bukan, biarlah itu menjadi urusan sampeyan-sampeyan yang punya daya dan kekuatan analisis di atas rata-rata. Saya hanya bisa menekankan bahwa tagar-tagar nggak jelas begitu adalah bagian dari aktivitas nyampah secara halus.
Nggak usah ngomong buzzer atau bukan, subjektif atau objektif, kalau membebali timeline pas disebut sampah. Kalau Twitter ini seumpama TPA, maka dari lama kapasitasnya sudah overload. Isinya orang-orang yang beradu tagar.
Layaknya orang nyampah, tentu muatan dan jenis sampahnya macam-macam. Ada yang membuang foto dirinya, kemudian dikasih tagar yang lagi diadu; ada juga yang tweet-nya nggak sesuai topik, tapi ditambahi dengan tagar yang diadu; ada pula yang benar-benar serius membela setengah mampus sosok dibalik tagar tersebut, sampai enteng menyerang secara personal lawannya.
Semua itu justru berpotensi besar tak cuma memenuhi Twitter, tetapi juga berpeluang jadi sampah di pikiran dan hati kita. Kalau di Twitter sih enak, bakal hilang dengan sendirinya. Tapi jika menumpuk di pikiran dan hati, maka telah berubah menjadi sampah yang dapat didaur ulang. Suatu saat sampah itu keluar lagi, dan jadi sampah lagi buat orang lain, kemudian didaur ulang, dibuang lagi, dan jadi sampah lagi. Begitu seterusnya.
Biasanya masyarakat ketika ada sampah penginnya dimusnahkan, dibikin tidak ada lagi di bumi agar tak membuatnya sesak. Memusnahkan sampah biasanya dengan cara membakarnya, menimbunnya ke tanah, atau memanfaatkannya. Membakar tukang nyampah dengan adu tagar tentu mustahil. Misalkan mau dimanfaatkan juga justru nyampah kembali.
Kita cuma punya kesempatan menimbunnya. Menanamnya kembali dalam-dalam ke pikiran kita. Tanpa sedikit pun mempunyai niatan campur tangan meramaikan adu tagar di Twitter. Setidaknya kita nggak nyampah berbalut kritik dan kebebasan berpendapat seperti mereka. Apalagi dengan cuitan yang kelewat wagu, nyeleneh, dan nggak menunjukkan sebagai warga negara yang ber-inteleksosbud.
Kendati demikian, saya pengin terima kasih juga kepada mereka. Dulu ketika ditanya “menulis itu apa?” oleh kawan seperjuangan, jawaban saya: menulis itu ibarat membuang sampah, telah berubah. Kini berkat orang-orang yang hobi perang tagar, saya sadar bahwa ada yang lebih cocok disebut membuang sampah daripada menulis, yaitu beradu tagar di Twitter.
by : Muhammad Arsyad (Mahasiswa)